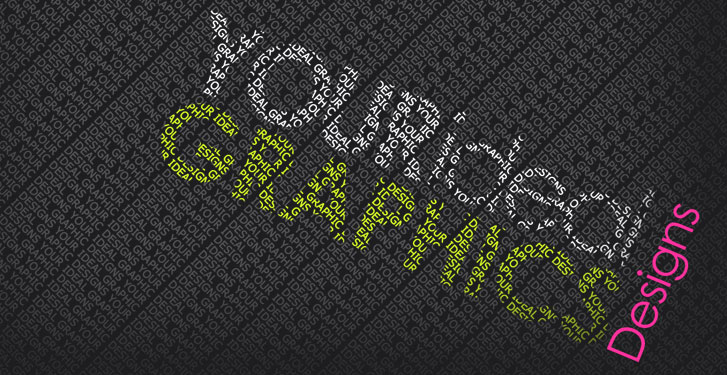- Selamat Beramal >>Good Work!
Hadith Dan Kedudukannya Dalam Madzhab Syiah
|
S.H. Nasr
 Sungguhpun banyak sekali kajian ilmiah telah dilakukan sejak abad ke-19 lagi, serta analisis-analisis dan penterjemahan-penterjemahan telah dibuat terhadap berbagai sumber keislaman, namun sejauh ini sangat sedikit sekali perhatian diberikan kepada himpunan sabda, khutbah, doa, ungkapan dan pengajaran keagamaan Syiah Imamiyyah. Memang benar, banyak dari kandungan himpunan hadith Syiah sama dengan kandungan dari kandungan himpunan hadith Ahlus Sunnah. Dengan demikian, jika himpunan hadith Ahlus Sunnah dikaji, maka himpunan hadith Syiah pun secara langsung telah tergarap. Mengingat bahwa hadith-hadith syiah memiliki bentuk, gaya, dan bauan khas, maka kajian tidak langsung terhadap kandungannya tidak akan dapat menggantikan kedudukan penterjemahan dan kajian langsung terhadap hadith-hadith itu sendiri.
Sungguhpun banyak sekali kajian ilmiah telah dilakukan sejak abad ke-19 lagi, serta analisis-analisis dan penterjemahan-penterjemahan telah dibuat terhadap berbagai sumber keislaman, namun sejauh ini sangat sedikit sekali perhatian diberikan kepada himpunan sabda, khutbah, doa, ungkapan dan pengajaran keagamaan Syiah Imamiyyah. Memang benar, banyak dari kandungan himpunan hadith Syiah sama dengan kandungan dari kandungan himpunan hadith Ahlus Sunnah. Dengan demikian, jika himpunan hadith Ahlus Sunnah dikaji, maka himpunan hadith Syiah pun secara langsung telah tergarap. Mengingat bahwa hadith-hadith syiah memiliki bentuk, gaya, dan bauan khas, maka kajian tidak langsung terhadap kandungannya tidak akan dapat menggantikan kedudukan penterjemahan dan kajian langsung terhadap hadith-hadith itu sendiri.Memang agak mengherankan, sungguhpun hadith-hadith Syiah mempunyai kedudukan yang penting sekali dalam perkembangan hukum dan ilmu kalam, maka Syiah maupun banyak bidang ilmu keintelektual (al-'ululmul aqliyyah), belum lagi peranannya dalam ketaqwaan dan kehidupan rohaniah, hingga kini sabda-sabda para Imam Syiah belum diterjemahkan. Sabda-sabda tersebut juga belum dikaji sebagai suatu himpunan khas sumber ilhami keagamaan dalam konteks umum Islam itu sendiri.
Kepustakaan hadith Syiah mencakup semua sabda Rasulullah Saww dan dua belas Imam, dari Ali bin Abi Talib sampai al-Mahdi. Dengan demikian, setelah al-Qur'an, hadith-hadith ini dipandang sebagai himpunan terpenting nash keagamaan bagi kaum Syiah. Seperti halnya dalam Ahlus Sunnah, bersama-sama al-Qur'an, hadith-hadith ini juga membentuk dasar semua ilmu keagamaan dalam segi intelektual mahupun ibadahnya. Tidak satu pun segi kehidupan dan sejarah kaum Syiah yang dapat dimengerti tanpa mempertimbangkan tulisan-tulisan ini.
Yang khas pada himpunan hadith Syiah adalah, sungguhpun merupakan bagian dari asas Islam, "susunannya" merentang selama lebih dari dua abad. Dalam Ahlus Sunnah, hadith merupakan sabda Rasulullah Saww. Menggunakan istilah hadith dalam Ahlus Sunnah berarti merujuk kepada hanya sabda Rasulullah Saww sedangkan dalam Syiah, sungguhpun hadith Nabi dan hadith para Imam dibedakan dengan jelas, keduanya merupakan satu himpunan yang tunggal. Hal ini bermaksud bahwa dari sudut pandangan tertentu, masa kerasulan dilihat oleh Syiah sebagai merentang melebihi kelaziman masa para rasul yang relatif singkat dalam berbagai agama.
Alasan sudut pandangan ini tentu saja terletak pada konsepsi Syiah tentang Imam. Istilah "imam", sebagaimana digunakan secara teknis dalam Syiah, berbeza dengan penggunaan umum istilah itu dalam bahasa Arab, yang bermaksud "pemimpin", atau, dalam teori politik Ahlul Sunnah, yang bermaksud khalifah itu sendiri. Digunakan secara teknis dalam Syiah, istilah itu merujuk kepada orang yang memiliki dalam dirinya "cahaya Muhammad" (al-nur al-Muhammadi) yang diturunkan melalui Fatimah, putri Rasulullah Saww, dan Ali, Imam pertama, kepada Imam-imam lainnya sampai al-Mahdi. Akibat adanya "cahaya" ini, Imam dipandang sebagai "suci" (maksum) dan memiliki pengetahunan sempurna tentang tatanan lahiriah maupun batiniah.
Para Imam adalah seperti serangkaian cahaya yang memancar dari "Matahari Kenabian" dan tidak pernah terpisah dari Matahari itu. Sedangkan Matahari itu merupakan asal-usul serangkaian cahaya itu. Apa pun yang mereka katakan berasal dari khazanah kearifan itu karena mereka merupakan suatu rantai dari realitas batiniah Rasulullah Saww, maka sebenarnya kata-kata merupakan kata-kata Nabi Saww. Itu sebabnya sabda-sabda mereka dipandang oleh Syiah sebagai suatu kesinambungan dari sabda-sabda Nabi, tepat seperti cahaya kemaujudan mereka dipandang sebagai kelanjutan cahaya kenabian. Dalam pandangan Syiah, keterpisahan sementara para Imam dari Nabi Saww sama sekali tidak mempengaruhi ikatan zat dan batiniah mereka dengan Nabi Saww, ataupun kelanjutan "cahaya kenabian yang merupakan sumber pengetahuan ilhami Nabi sendiri dan para Imam.
Konsepsi metafizikal ini merupakan alasan mengapa kaum Syiah menjadikan hadith-hadith para Imam, yang terungkap selama lebih dari dua abab, dengan hadith-hadith Nabi Saww itu sendiri sebagai satu keseluruhan tunggal. Hai ini juga membedakan antara konsepsi Syiah dan Ahlus Sunnah tentang hadith. Sebenarnya kandungan hadith dalam himpunan-himpunan Ahlus Sunnah dan Syiah adalah sangat mirip. Namun keduanya menyoroti realitas rohaniah yang sama. Tentu saja rangkaian perawian yang diterima oleh dua madzhab ini tidaklah sama. Sungguhpun para perawi sabda-sabda Nabi SAWA berbeda, sebenarnya hadith-hadith yang dicatat oleh sumber Ahlus Sunnah dan Syiah banyak sekali persamaannya. Perbedaan utamanya adalah karena Syiah berpandangan bahwa para Imam merupakan kelanjutan dari kewujudan Nabi Saww dan kerana itu sabda-sabda para Imam merupakan pelengkap sabda-sabda Nabi Saww.
Dalam banyak hal, hadith-hadith para Imam bukan saja sebagai kelanjutan tetapi juga sebagai pengulas dan penjelas terhadap hadith-hadith Nabi Saww, dan sering bertujuan menyingkapkan ajaran-ajaran mutasyabihah dalam Islam. Banyak dari hadith-hadith ini, seperti hadith-hadith Nabi Saww, membahas segi-segi praktis kehidupan dan syariat. Dan banyak pula yang membahas metafizika-metafzika murni sebagaimana juga dibahas oleh sebahagian hadith Nabi Saww khususnya hadith-hadith qudsi. Di samping itu hadith-hadith lain para Imam juga membahas sudut-sudut ibadah dan mengandungi beberapa do'a termasyhur yang telah diucapkan selama berabad-abad oleh Ahlus Sunnah maupun Syiah. Sebahagian hadith itu membahas berbagai ilmu batiniah. Dengan demikian, hadith-hadith itu meliputi masalah-masalah duniawi dalam kehidupan seharian dan masalah makna kebenaran itu sendiri. Disebabkan oleh sifat hadith-hadith itu dan juga kenyataan bahawa seperti tasawuf, hadith-hadith itu maujud dari dimensi batiniah Islam,maka hadith-hadith itu telah berbaur selama beradab-abad dengan jenis-jenis tertentu tulisan kesufian. Mereka juga telah dipandang sebagai esoterisisme (kebatinan) Islam oleh kaum sufi, kerana para Imam itu dipandang oleh kaum sufi sebagai kutub-kutub rohaniah, pada masa mereka. Mereka wujud dalam silsilah rohaniah berbagai tarekat kesufian dan malah tarekat-tarekat yang telah tersebar hanya di kalangan kaum Ahlul Sunnah.
Disebabkan oleh karakter kandungan-kandungannya, hadith -hadith ini telah mempengarui hampir setiap cabang ilmu dalam Syiah mahupun kehidupan seharian umat. Fiqh Syiah mendasarkan dirinya langsung pada himpunan hadith ini di samping al-Quran Suci. Teologi Syiah tidak akan dapat dimengerti tanpa mengetahui hadith-hadith ini. Ulasan-ulasan Syiah tentang al-Quran banyak tertumpu pada hadith-hadith itu. Begitu juga ilmu-ilmu kealaman seperti sejarah kealaman atau kimia berkembang dari hadith-hadith itu. Hadith-hadith ini telah menjadi sumber renungan tentang tema-tema metafizikal tertinggi selama berabad-abad. Dan beberapa madzhab metafizikal dan falsafah dalam Islam bersumberkan terutamanya dari hadith-hadith ini. Falsafah keislaman Shadruddin Syirazi (Mulla Shadra) sesungguhnya tidak akan dapat dimengeri tanpa merujuk kepada hadith-hadith Syiah. Salah satu karya terbesar metafizikal Shadruddin adalah ulasannya yang belum selesai tentang sebahagian dari empat hadith pokok terpenting Syiah iaitu al-Kafi oleh al-Kulaini.
Didalam himpunan hadith Syiah terdapat karya-karya tertentu yang perlu dipaparkan secara terpisah. Yang pertama adalah Nahjul Balaghah karya Imam Ali bin Abi Talib yang dihimpun dan disusun oleh ulama Syiah pada abad ke-4H/10M iaitu Sayyid Syarif al-Radhi. Mengingat pentingnya karya ini dalam Syiah mahupun bagi para pencinta bahasa Arab, maka amat menghairankan betapa sedikit sekali perhatian telah diberikan kepadanya. Banyak penulis kenamaan dalam bahasa Arab, seperti Taha Husain dan Kurd Ali menyatakan dalam autobiografi-autobiografi mereka bahwa mereka telah menyempurnakan gaya mereka dalam menulis Arab melalui kajian terhadap Nahjul Balaghah, sementara generasi demi generasi para pemikir Syiah telah merenungkan dan mengulas maknanya. Lagi pula, doa-doa dan ungkapan-ungkapan lebih pendek dari karya ini telah menyebar luas di kalangan umat dan telah masuk ke dalam kepustakaan klasik dan rakyat, bukan saja dalam bahasa Arab, tetapi juga Persia dan melalui pengaruh Persia beberapa bahasa masyarakat Islam yang lainnya seperti Urdu.
Selain memuat nasihat rohaniah, ungkapan-ungkapan moral dan petunjuk-petunjuk politik, Nahjul Balaghah juga mengandung beberapa risalah luar biasa mengenai metafizika, khususnya mengenai masalah Tauhid. Ia memiliki metodologi pemaparan dan kosakata teknis tersendiri yang membedakannya dari berbagai madzhab-Islami metafizika.
Dalam jangka waktu yang lama, para sarjana Barat menolak untuk menerima kesahihannya sebagai karya Ali bin Abi Talib, dan menisbahkannya kepada Sayyid Syarif al-Radhi, sungguhpun gaya karya al-Radhi sendiri sangat berbeda dengan gaya Nahjul Balaghah. Namun demikian sejauh menyangkut sudut pandangan Syiah, kedudukan Nahjul Balaghah dan penulisnya dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui suatu percakapan yang terjadi delapan belas atau sembilan belas tahun yang silam antara Allamah Thabatabai dan Henry Cobin ,pernah berkata kepada Allamah Thabatabai selama diskusi-diskusi harian mereka di Teheran."Sarjana-sarjana Barat menyatakan bahwa Ali bukanlah penulis Nahjul Balaghah. Bagaimana pandangan anda, dan siapakah kiranya menurut anda penulis karya ini?" Allamah Thabathabai mengangkat kepalanya dan menjawab dengan lemah lembut dan tenang sebagaimana biasa,"Bagi kami siapa pun yang menulis Nahjul Balaghah, dialah Ali, meskipun dia hidup seabad yang silam."
Karya penting kedua dalam himpunan hadith Syiah adalah al-Sahifah al-Sajadiyyah karya Imam Keempat Ali Zainal Abidin, yang digelar al-Sajjad. Sebagai saksi tragedi Karbala yang telah meninggalkan pada jiwanya suatu kesan yang tidak terhapuskan. Imam keempat ini menuangkan kehidupan rohaniahnya dalam suatu simfoni doa-doa indah yang telah menyebabkan Sahifah disebut "Mazmur Ahlul Bayt Rasulullah". Doa-doa ini membentuk suatu bahagian dari kehidupan keagamaan seharian bukan sahaja kaum Syiah tetapi juga kaum Ahlul Sunnah, yang mendapati doa-doa itu dalam banyak buku pedoman doa termasyhur di kalangan Ahlul Sunnah.
Yang juga penting dalam kehidupan hadith Syiah adalah hadith-hadith Imam kelima, keenam, dan ketujuh. Dari merekalah sejumlah terbesar hadith telah dicatat. Imam-imam ini hidup pada akhir Dinasti Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyyah.Pada masa-masa ini, akibat perubahan-perubahan dalam kekhalifahan, kuasa pusat menjadi lemah, sehingga para Imam itu dapat berbicara lebih terbuka, dan juga mendidik lebih banyak murid. Jumlah murid. sama ada Syiah ataupun Sunni, yang dididik oleh Imam keenam, Ja'far al-Sadiq, diperkirakan seramai empat ribu orang. Beliau meninggalkan sejumlah besar hadith yang berkisar dari masalah hukum hinggalah ilmu-ilmu batiniah.
Hadith-hadith Rasulullah dan para Imam tentu saja merupakan suatu sumber tetap renungan dan perbahasan oleh ulama-ulama Syiah di sepanjang masa. Namun khususnya dalam jangka masa berikut dari sejarah Syiah yang bermula dengan Sayyid Haidar Amuli , ulama besar pada masa Safawiyah seperti Mir Damad dan Mulla Shadra hingga kini, hadith-hadith ini telah bertindak sebagai sumber aktual bagi metafizika dan filsafat mahupun ilmu-ilmu hukum dan al-Quran. Ulasan-ulasan Mulla Shadra, Qadhi Said al-Qummi dan banyak lagi ulasan atau himpunan-himpunan hadith Syiah ini merupakan di antara karya-karya besar dalam pemikiran Islam. Akhirnya, falsafah dan teosofi keislaman benar-benar tidak akan dapat dimengerti tenpa merujuk kepada hadith-hadith tersebut
(Dipetik dari: S.H. Nasr untuk pengantar buku "A Shi'ite Anthologi" karya Allamah M.H. Thathabatai terbitan Ansariyan Publication, Qum, 1982; Islam Syiah, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,Lampiran V).
Pohon Tawhid
|
Ust. Abdullah Assegaf
 Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu mengingatnya. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tegak barang sedikitpun. (Ibrahim: 24-26)
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu mengingatnya. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tegak barang sedikitpun. (Ibrahim: 24-26)Dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (al-A’râf: 58)
Negeri yang baik (subur) akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik, kokoh, dan subur pula, dengan izin Allah Swt. Begitu juga, negeri yang buruk tentunya tidak akan menumbuhkan kecuali tumbuhan yang buruk, kering, dan lemah.
Di hari kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saww berkata kepadanya, “Engkau adalah pembagi surga dan neraka.” Rasulullah saww kemudian menambahkan, “Siapa saja yang menempatkan cinta(nya) kepada Amirul Mukminin, maka ia mukmin. Dan tidak ada orang yang menempatkan kebencian kepadanya, kecuali ia munafik.”
Begitulah kelahiran salah seorang di antara Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah Swt dengan firman-Nya: Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sesuci-sucinya. (al-Ahzâb: 33) Ya, kelahiran seseorang yang Allah Swt mengatakan tentangnya: Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka rukuk. (al-Mâidah: 55)
Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, “Wilayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah benteng penjagaan-Ku, dan siapa saja yang masuk ke dalam benteng penjagaan-Ku, maka mereka akan selamat dari siksa-Ku.”
Firman Allah Swt sebelumnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan firman Allah Swt yang menceritakan tentang tumbuhan yang baik. Pada ayat tersebut, Allah Swt mengawalinya dengan kata-kata: Bumi yang baik…(dan seterusnya sampai akhir ayat). Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Swt dengan tumbuhan yang baik itu?
Allah Swt menjelaskan bahwa tumbuhan yang baik adalah tumbuhan kokoh, yang akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya menjulang tinggi ke langit, dan dari pohon ini merebak buah-buahan yang banyak sekali manfaatnya. Tumbuhan yang baik (sajarah al-thayyibah) adalah sajarah al-tauhid (pohon tauhid). Yakni, adanya kekuatan tauhid pada diri manusia. Ya, tauhid ibarat pohon dan manusia adalah bumi (tanah, negeri) di mana pohon ini tumbuh.
Apabila pohon tersebut tumbuh pada tempat atau tanah yang baik, maka ia akan berdiri dengan tegak dan kokoh pada diri manusia dan menghasilkan buah yang banyak sekali manfaatnya. Pohon tauhid akarnya berada di hati manusia dan cabangnya muncul pada amal dan perbuatannya. Ketika akarnya mulai menghunjam dan berpegang kuat pada tanah yang kokoh dan baik, maka batangnya akan bertumbuh merambat ke langit dan “bertemu” dengan Allah Swt setelah sebelumnya menyingkirkan segala hal yang menghalangi kehidupannya.
Sama halnya, ketika manusia tidak berhubungan dengan Allah Swt; ketika berbagai permasalahan, problem, dan tuntutan kehidupan mendominasi manusia itu sendiri; ketika manusia mulai meracuni dirinya dengan berbagai pelanggaran dan kemaksiatan, maka yang pertama kali dirusak adalah akar dari pohon tauhid tersebut. Akar di mana batang dan buah berasal daripadanya. Lemah dan busuknya akar akan menumbangkan batang dan pohon yang menjulang tinggi dan “menemui” Allah Swt. Rusak dan keringnya akar akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan batang dan buah yang ada, sehingga pohon tersebut tidak hidup dengan baik dan tidak menghasilkan buah yang ranum.
Setiap manusia bisa saja memiliki nilai tauhid, namun tidak setiap orang akan “bertauhid”. Ia, pada taraf tertentu, dapat meraih manfaat dari nilai tauhid yang dimilikinya, namun ia tidak akan selalu dapat memperoleh manfaat dari tauhid yang ada pada dirinya.
Mungkin saja ia memiliki kesadaran untuk menghamba kepada Allah Swt, memiliki kesadaran untuk hanya tunduk dan takut kepada Allah Swt, tetapi apabila kesadaran ini tumbuh di lahan yang buruk atau penuh dengan racun kemaksiatan, maka perjalanan menuju Allah Swt tidak akan pernah terjadi. Sebab, ketika kesadaran bahwa ia harus tunduk kepada Allah Swt tertanam di hatinya, maka sebagai konsekuensinya ia harus menyingkirkan ketundukan kepada selain Allah. Akibatnya, mungkin secara fisik ia akan menderita. Sebab, ketundukan kepada Allah Swt melazimkan seseorang untuk memiliki ketegasan pada setiap persoalan, pada setiap nilai keyakinannya.
Ketika manusia memenuhi jiwanya dengan kemaksiatan, maka akar kesadaran tauhid yang tumbuh dalam dirinya akan sangat kecil, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menumbuhkan dan menegakkan batang yang besar. Kalaupun batang tersebut muncul ke permukaan, ia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan dan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalanginya.
Kita dapat bayangkan itu dalam kehidupan kita kini yang didera oleh konflik antara satu pihak dengan pihak lainnya, didera oleh kemiskinan dan kekurangan, sementara tuntutan konsumtif selalu ditumbuhkan di tengah masyarakat. Media massa selalu mendidik kita untuk mengejar dan mengejar kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier. Dari sisi ini saja, kita benar-benar mengalami kesulitan untuk mengatasinya, kita sulit untuk tidak bermaksiat. Islam tidak melarang kita untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier kita, namun Islam melarang kita bila kebutuhan itu dipenuhi dengan cara bermaksiat kepada Allah Swt.
Ada istilah konyol yang sering diungkapkan orang, “Mencari (nafkah) yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal.” Kata-kata ini dan angan-angan panjang kita atas kehidupan dunia ini telah membuat ruang yang semakin lebar bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Swt. Ini seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin, “Harapan saya dan dunia ini bersekutu, ya Allah; bekerja sama untuk menumbangkan saya dalam kemaksiatan (dalam tindakan yang melanggar keinginan-Mu).”
Dalam wasiatnya, Rasulullah saww berkata, “Berhati-hatilah kalian dengan hijau-hijauan.” “Apa yang dimaksud dengan hijau-hijauan itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Wanita yang elok (cantik) tetapi ia berasal dari sumber yang buruk.” Maksudnya, setiap manba’ (tempat bertumbuh) yang buruk—meskipun pohon yang ditanam baik mutunya—tidak akan dapat menghasilkan kebaikan apapun. Manakala hati dan jiwa ini kotor, maka tauhid, kalimat lâ ilâha illallâh, menjadi tidak berguna.
Manakala benak manusia hanya tertuju pada dunia, maka memori yang ada di kepalanya hanyalah mobil, rumah, televisi, atau segala hal yang berhubungan dengan dunia, dan tidak tersisa sedikit pun laci untuk memikirkan masalah ketidakadilan, misalnya. Ia hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk mengganti barang-barang yang dimilikinya dengan model terbaru; hanya itulah isi kepalanya.
Karena itu, apa artinya tauhid yang tumbuh dalam pikiran manusia dan tidak lebih dari sebesar jari kelingking kita, sementara ia harus menanggung pertumbuhan batang yang digambarkan luar biasa oleh Allah Swt. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa betapa panjangnya perjalanan untuk sampai kepada Allah Swt dan alangkah sempitnya waktu yang kita sediakan.
Allah menyatakan dalam firmannya: Yâ ayyuhal insân kadihun ilâ rabbik. Kadih adalah perjalanan sangat sulit dan panjang yang harus ditempuh manusia. Dalam pada itu, tajuk pohon yang harus sampai kepada Allah Swt adalah berupa amal perbuatan manusia; bagaimana mengatasi problem, merengkuh kebenaran, meraih ridha Allah Swt. Ini adalah batang dan tajuk yang besar. Kalau akarnya tidak besar, maka bagaimana mungkin ia dapat menjulang tinggi. Mungkin, dengan ketinggian satu meter meter saja, ia akan sudah tumbang. Sementara, Allah Swt mengatakan bahwa ia menjulang tinggi, kokoh, kuat, dan tidak goyah dalam hati kita.
Karena itu, kita sering menemukan orang yang mengucapkan kalimat tauhid, mengatakan tiada tuhan selain Allah Swt, namun itu bertumbuh di comberan hatinya yang sakit atau di lahan batinnya yang kering dan tandus.
Oleh karena itu, mempersiapkan, menyuburkan, dan mengolah lahan bagi pertumbuhan tanaman tauhid merupakan sebuah kemestian. Bagi orang yang memang lahannya sudah kering bak padang pasir, janganlah ia berkhayal untuk dapat menumbuhkan tanaman apapun, sebelum mengolah dan memupuknya agar menjadi subur. Artinya, meskipun tanah itu kering, itu bukan berarti tanaman tauhid tidak akan bisa tumbuh (karena masih bisa diolah lagi).
Kalau kita tengok lintasan sejarah Islam, maka kita akan mengenal seorang budak hitam yang dilahirkan dari hasil perzinahan. Budak tersebut bernama Haitsam. Lahan dirinya memang kering untuk menumbuhkan pohon tauhid, namun lantaran lahan kritis itu diolah dengan sungguh-sungguh, tanaman itu pun dapat bertunas dan bertumbuh dengan baik. Apa yang akhirnya terjadi? Haitsam ditahan dan disalib oleh penguasa zalim bani Umayah (Marwan bin Hakam) di lapangan. Apa buah pohon tauhid itu? Selama penyaliban, dari mulutnya senantiasa terlontar kata-kata hikmah dan kisah tentang berbagai kejadian di alam ini. Setiap hari orang berkumpul dan mendengarkan apa yang disampaikan Haitsam. Setiap mengakhiri pidatonya, ia selalu berkata, “Saya mengetahui semuanya ini hanya lantaran lima tahun saya bersama Ali bin Abi Thalib.”
Mempersiapkan lahan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tugas manusia, yaitu mengikuti panggilan fitrah untuk bertahan dan menahan diri atas hal-hal yang haram dan halal, mulai dari perut, penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, pada batasan fiqh saja. Janganlah kita terlampau bingung dengan masalah, misalnya, “Saya ini shalat dalam keadaan suci atau belum?” Semestinya kita bingung dengan masalah, “Apakah telinga saya ini sudah suci dari mendengarkan ghibah, lisan ini sudah suci dari melontarkan fitnah?” Sebab, kalau nilai-nilai ini selalu kita usahakan agar tetap terjaga, maka demi sedikit berbagai macam penyakit dalam diri kita akan terkikis.
Semua itu adalah upaya kita untuk menghindar dari murka Allah Swt. Ya, berhenti dari perbuatan haram adalah pupuk paling istimewa untuk menyuburkan tanah tauhid dalam diri manusia. Kita tidak perlu bercerita tentang bagaimana berbuat baik dulu, tetapi bagaimana menghidupkan diri kita dengan membuat tanah tersebut subur lantaran tauhid, sehingga pohon tauhid yang ada dalam diri kita ini tumbuh semakin kokoh dan kuat.
Dalam lintas sejarah disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Umar bin Khattab menghadap Hajjaj bin Yusuf (algojo Yazid paling garang), dari rumah pakaiannya telah basah dengan kencing lantaran ketakutan. Sesampainya di hadapan Hajjaj, ia menyatakan baiatnya (kepada Yazid) melalui sang algojo ini. Ia melakukan itu dengan tangan kanannya dan kaki ditekuk, sementara Hajjaj menyambutnya dengan salah satu kakinya. Padahal kita mengetahui bahwa Abdullah bin Umar adalah salah seorang tokoh sufi, namun, apa yang telah dilakukannya?
Hal itu kontras dengan yang dilakukan oleh Said bin Jubair, ketika ia dihadapkan kepada orang yang sama, Hajjaj bin Yusuf. Ketika Said ditanya yang mana yang lebih dicintainya, Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali bin Abi Thalib, ia menjawab, “Siapa yang paling dicintai Allah, maka saya cinta kepadanya.” Maksudnya, “Cinta saya mengikuti cintanya Allah Swt; yang paling utama dalam pandangan Allah Swt, itulah yang paling utama dalam pandangan kami.”
Segala yang disampaikan Said bin Jubair di hadapan Hajjaj bin Yusuf, si terkutuk, tidak lain hanyalah tauhid yang dimilikinya. Apa yang terjadi ketika Hajjaj bin Yusuf memerintahkan agar Said bin Jubair dibunuh (dipenggal) dengan dihadapkan ke Kiblat? Ia malah membaca ayat: innî wahjahtu wajhiya lilladzî fatharas samâwâti wal ard (saya menghadapkan wajah saya pada yang menciptakan langit dan bumi).
Hajjaj memerintahkan agar ia dipalingkan dari Kiblat. Said bin Jubair menjawabnya dengan membaca ayat: kemanapun engkau berpaling, di situlah wajah (berhadapan dengan) Allah Swt. Hajjaj kemudian menyuruh agar menelungkupkan wajahnya ke tanah. Di tanah ia berkata (membaca ayat): darinya Engkau ciptakan (aku) dan darinya pula aku Engkau bangkitkan dan (darinya pula aku) dikembalikan.
Ya, semuanya ia kembalikan kepada Allah Swt. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Hajjaj memerintahkan untuk memotong lidah Said bin Jubair terlebih dahulu. Kemudian mereka menggergaji bagian punggungnya. Darah yang mengalir dari tubuh Said bin Jubair menjadi saksi atas ketauhidannya. Darah itu membentuk tulisan: lâ ilâha illallâh Muhammad al-Rasûlullâh.
Begitulah, Allah Swt telah mengatakan bahwa wilayah (kepemimpinan) Ahlul Bait adalah benteng pertahanan Allah Swt. Benteng Allah Swt inilah yang menjadikan manusia selamat dari azab Allah Swt, di dunia maupun akhirat.
Setiap tindakan manusia di dunia akan mendatangkan balasan, entah balasan baik atau buruk. Bahkan perbuatan baik kita bisa berakibat negatif pada diri kita, sebagaimana perbuatan buruk akan berakibat negatif pada diri kita. Ketika kita berbicara tentang kehidupan di dunia, maka tidak semua perbuatan baik mengakibatkan dampak positif bagi diri kita. Sebagai contoh adalah upaya yang dilakukan oleh Imam Khomeini dengan revolusinya. Dari satu sisi, itu buruk, sebab, berakibat pada embargo ekonomi dan senjata yang dilakukan musuh-musuh Islam, sehingga perekonomian bangsa Iran menjadi terpuruk.
Apa yang didakwahkan oleh Rasulullah saww telah menjadikan beliau diasingkan (diblokade) selama tiga tahun, sehingga untuk makan saja beliau harus mengumpulkan pucuk dedaunan atau terpaksa mengganjal perut beliau dengan batu. Inilah penderitaan duniawi yang merupakan konsekuensi dari perjuangan yang beliau lakukan.
Ya, kalau kita berbicara pada takaran dunia, perbuatan baik yang kita lakukan dapat berakibat negatif. Meskipun, dari sisi pandang yang lain, ia merupakan hal yang positif. Nabi Musa as mengatakan bahwa azab Allah Swt itu bisa terjadi di dunia ini. Setiap tindakan kita dapat mendatangkan atau melahirkan azab bagi kita.
Sebagaimana, yang terjadi pada Firaun dan Nabi Musa as. Beliau as berkata, “Sesungguhnya saya memiliki dosa terhadap Firaun (innalî ‘alaihi dzanbun).” Maksudnya, Nabi Musa as memiliki dosa terhadap Firaun, sehingga Penguasa Mesir ini harus mengejar, menyakiti, atau membunuh beliau. Dengan demikian, dakwah Nabi Musa as, dari satu sisi pandang tertentu, telah mendatangkan azab pada diri Nabi Musa as.
Meskipun demikian, apa pendapat Amirul Mukminin Ali bin Abi Tahlib? Beliau berkata, “Aku dapat bersabar atas azab-Mu, namun bagaimana mungkin aku dapat bersabar dari berpisah dengan-Mu (shabartu alâ adzâbik fa kaifa ashbirû alâ firâqik).” Maksudnya, “Ya Allah, atas siksa-siksa-Mu yang lain, aku akan bersabar. Meskipun wanita yang paling kukasihi, puteri Nabi-Mu (Fathimah), disakiti sedemikian rupa—sementara aku memiliki emosi, kekuatan, dan pedang; aku mampu memenggal kepala penguasa zalim yang menyakiti puteri Nabi-Mu itu—namun aku dapat bersabar akan hal itu. Sebaliknya, untuk berpisah dari ridha-Mu, menderita siksaan berpisah dengan-Mu, aku tidak akan mampu sabar menanggungnya.
Ya, keberadaan manusia dalam benteng Allah Swt (wilayah) akan menjadikannya semakin kuat menghadapi segala musibah yang mendera. Sebab, Rasulullah saww bersabda, “Siapa saja yang menempatkan cintanya pada Ahlul Bait, maka saat itu ia mengenakan jubahnya musibah.” Begitulah, musibah adalah sesuatu yang akan selalu berjalan bersama orang yang berada dalam wilayah Ahlul Bait. Dengan demikian, mereka akan banyak memperoleh pelajaran dari kehidupan ini. Namun, musuh paling utama bagi mereka adalah keinginan-keinginan pribadi yang melambungkan angan-angan dalam diri mereka, sehingga menjadi abai terhadap kewajiban-kewajibannya.
Bukti telah terurai di sebalik "Tirai aLQuran"
Mengapa nama para Imam Maksum As tidak dicantumkan secara jelas dalam Al-Qur’an?
Perlu diketahui bahwa kendati nama para Imam Maksum As tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an, namun dalam sabda-sabda Nabi Saw disebutkan secara jelas nama para Imam Maksum As, khususnya nama Imam Ali As yang merupakan proyeksi jelas dari hadis al Ghadir dan sebagai pengumuman resmi akan kekhalifahannya. Hadis al Ghadir, dari aspek sanadnya termasuk hadis yang mutawatir dan dari sisi dilâlah-nya (petunjuknya) merupakan bukti-bukti jelas akan imâmah Imam Ali As.
Terlepas dari hal ini, dalam Al-Qur’an juga terdapat ayat-ayat yang turun berkenaan dengan Imam Ali As dimana yang paling penting di antaranya adalah surat al-Maidah ayat 55 yang artinya:”Sesungguhnya wali kalian adalah hanya Allah Swt dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan shalat serta memberikan zakat dalam keadaan ruku’”. Dalam kitab-kitab tafsir, sejarah dan riwayat-riwayat, baik Syi’ah ataupun Sunni, disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Imam Ali As yang sedang ruku’ sambil menginfakkan cincinnya dan bukti luarnya itu tidak ada yang lain kecuali Imam Ali As, oleh itu meskiAl-Qur’an tidak menyebutkan secara transparan nama Imam Ali As, namun ia telah menunjukkan hal itu secara jelas.
Namun bahwa mengapa nama Imam Ali itu tidak disebutkan secara terbuka? Minimal ada dua jawaban yang dapat disuguhkan di sini. Pertama: Secara mendasar, Al-Qur’an itu (diturunkan) untuk menjelaskan seluruh permasalahan itu secara universal, dengan bentuk kaidah dan pokok, bukan menjelaskan secara rinci dan detil seluruh permasalahan. Dan demikianlah yang berlaku pada beberapa teori-teori Al-Qur’an. Terkait hal ini, ketika Imam Shadiq As ditanya: Mengapa nama para Imam As tidak disebutkan secara terbuka dalam Al-Qur’an, beliau menjawab: sebagaimana halnya Allah Swt menurunkan perintah shalat, zakat, haji secara universal tanpa menjelaskan perinciannya, bahkan Rasulullah Saw sendiri yang menjelaskan dan menerangkan cara pelaksanaan dan rincian hukum-hukumnya. Demikian pula dengan masalah wilâyah, Rasulullah Saw sendiri yang menjelaskan serta memaparkan ihwal kekhalifahan Imam Ali As dan Ahlulbait As tanpa perlu disebutkan nama para Imam Maksum As satu per satu dalam Al-Qur’an. Kedua: Pada masalah seperti ini, karena diprediksikan banyak orang yang akan menentang, maka jalan terbaik dan maslahat adalah Al-Qur’an menjelaskan hal ini secara tidak transparan dan cukup dengan isyarahdan kinâyah (kiasan) saja, lantaran kemungkinan penentangan atas masalah keimamahan para Imam Maksum As bisa melebar sampai kepada menentang Al-Qur’an itu sendiri dan juga prinsip serta pokok agama, yang tentu saja hal ini akan sangat berbahaya bagi umat Islam secara keseluruhan; artinya betapa banyak orang-orang yang menentang wilâyah Imam Ali As yang karena penentangan itu –jika ada ayat yang secara transparan dan terbuka menjelaskan ihwal wilâyah beliau As– mereka berani dan nekad merubah dan membelokkan ataupun menghapus ayat tersebut, dan ketika itu nilai Islam sebagai agama penutup dan Al-Qur’an sebagai kitab suci yang abadi akan dicemooh dan dihina.
Selain itu, perlu dicamkan baik-baik bahwa kalau Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya: ”Kami telah menurunkan Al-Qur’an dan kami pulalah yang akan menjaganya”. Salah satu cara menjaga Al-Qur’an adalah memberantas seluruh motivasi-motivasi untuk menentang dan distorsi tersebut secara alami. Dengan demikian dalam Al-Qur’an, pertama: tidak dijelaskan secara transparan ihwal wilâyat dan juga tidak disebutkan dengan jelas nama beliau (Ali As), kedua: ayat-ayat yang ada kaitannya dengan wilâyatImam Ali As dan ayat tabligh yang merupakan ayat yang mengumumkan langsung secara resmi atas wilâyah dan khilâfah Imam Ali As dan juga ayat tathir yang mengandung kemaksuman (terhindar dari segala bentuk dosa) Ahlulbait As, yang terletak di antara ayat-ayat yang lahir tidak punya relasi sama sekali dengan bahasan yang ada, sehingga semaksimal mungkin dapat mengatasi adanya keinginan dan motivasi untuk mengganti dan merubah (Al-Qur’an) dan karena itu sepanjang sejarah, Al-Qur’an selalu terjaga dan terpelihara dari segala macam distorsi.
Terlebih dahulu ada poin penting yang perlu kita camkan baik-baik. Pertama: nama para Imam Maksum As secara jelas disebutkan dalam sabda-sabda Nabi Saw, khususnya nama mulia Imam Ali As yang telah dijelaskan Rasulullah Saw ihwal wilâyat dan khilâfah Imam Ali As, salah satu di antaranya adalah pada awal pengangkatan Rasulullah Saw menjadi nabi, ketika beliau Saw menyampaikan risalahnya kepada keluarga, kaum dan sanak famili, Rasulullah Saw bersabda:”Orang yang paling pertama beriman kepadaku,maka ia akan menjadi wali, wazir dan penggantiku”, dan tidak ada satu orang pun yang menyambut kecuali Imam Ali As dan pada akhirnya Rasulullah Saw bersabda pada Imam Ali As: “Setelahku, engkaulah yang akan menjadi washi, wazir dan khalifah”.[1] Riwayat lain adalah “hadis al Ghadir” yang dijelaskan Nabi Saw secara terang-terangan:”Man kuntu maulaahu fa ‘aliyyun maulaahu” (Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya maka Ali As menjadi pemimpin baginya).[2] Dan juga hadis “manzilah” dimana Rasulullah Saw bersabda kepada Imam Ali As:” Engkau (wahai Ali As) bagiku (Nabi Saw) laksana Nabi Harun As bagi Nabi Musa As, kecuali bahwa tidak ada nabi setelahku”.[3]
Hadis-hadis Nabi Saw tentang khilafah dan kepemimpinan Imam Ali As itu kebanyakannya adalah mutawatir dan hal ini telah banyak diisyarahkan dalam banyak kitab, baik dari pihak Syiah atau pun Sunni.[4] Dalam hadis lain, Rasulullah Saw menyebutkan dan menjelaskan semua nama para Imam Maksum As dari Imam Ali As sampai Imam Zaman kepada Jabir bin Abdullah al Anshari.[5]
Jadi poin yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa kendati nama para Imam Maksum As tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur’an. Akan tetapi Nabi Saw, yang menurut Al-Qur’an seluruh ucapannya adalah hak dan wahyu,[6] menyebutkan dengan jelas nama para Imam Maksum As dan beliau menegaskan dan menekankan keimamahan dan kekhalifahan mereka itu.
Kedua: Dalam Al-Qur’an telah disinggung tentang wilâyah Imam Ali As, meskipun tidak disebutkan dengan jelas nama beliau. Mayoritas para mufassir, baik dari kalangan Syi’ah maupun Ahlusunnah, mengakui bahwa telah turun ayat yang berkenaan dengan Imam Ali As, dan tidak ada sosok lain kecuali Imam Ali As[7] dan ayat tersebut adalah surat al-Maidah ayat 55, dimana Allah Swt berfirman:”innamâ waliyyukumullâhu warasûluhu walladzîna âmanû yuqiimuunashshalah wayu’tuunazzakaah wa hum râki’ûn” (Sesungguhnya wali kalian adalah hanya Allah Swt dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan shalat serta memberikan zakat dalam keadaan ruku’).
Dengan melihat bahwa dalam Islam kita tidak memiliki perintah dan aturan dimana manusia harus memberi zakat ketika sedang ruku’, maka jelaslah kalau ayat ini menunjukkan pada suatu kejadian yang hanya terjadi sekali kali, dan kejadian tersebut adalah tatkala Imam Ali As sedang ruku’ dan datang seorang pengemis meminta bantuan, Imam Ali As menunjuk ke tangannya, pengemis itu pun datang dan mengeluarkan serta mengambil cincin dari tangan Imam Ali As lantas pergi.[8] Berdasarkan hal ini ayat tersebut menyatakan dengan menggunakan kata “innamâ” [9], hanya Allah Swt dan Nabi Saw serta Imam Ali As yang berhak menjadi wali dan pemimpin kalian wahai kaum muslimin dan tidak ada orang lain yang memiliki wilayah atas kalian selain mereka.
Sampai disini jelas bahwa nama para Imam Maksum As dengan jelas ada dalam sabda-sabda Nabi Saw dan juga Al-Qur’an telah mengisyarahkan tentang wilayah dan khilafah Imam Ali As, dimana kalau ada seorang periset objektif dan hanya kebenaran yang dicari maka dengan cepat bisa memahami bahwa yang dimaksud Nabi saw dengan khilafah dan imamah setelah beliau Saw adalah khilafah Imam Ali As dan Ahlulbaitnya yang suci. Adapun masalah kenapa nama para Imam Maksum itu tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur’an, ada dua dalil yang bisa kita sodorkan disini:
1. Sejatinya Al-Qur’an itu diturunkan untuk menjelaskan segala masalah dalam bentuk yang universal dan berupa kaidah dan pokok, bukan untuk menjelaskan seluruh perkara secara terperinci dan detil, sebagaimana dalam banyak hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan furu’ (cabang dan ranting).
Jawaban ini diterangkan dalam sebuah riwayat dari Imam Shadiq As[10] dan untuk memperkuat pernyataan tersebut, Imam Shadiq As memberikan tiga contoh: pertama berkenaan dengan shalat, Al-Qur’an menjelaskan hal ini secara universal dan tidak menjelaskan tentang bagaimana kualitas dan kuantitas setiap shalat tersebut, namun Nabi Saw menerangkan kepada seluruh kaum muslimin tentang tata cara pelaksanaan dan jumlah raka’at shalat tersebut. Juga beliau memberikan contoh mengenai zakat bahwa dalam Al-Qur’an hanya disebutkan secara intinya saja, namun beliaulah Saw yang menetapkan apa-apa saja yang perlu dikeluarkan zakatnya dan ukuran nisab setiap dari sesuatu itu. Dan ketiga beliau Saw juga mengisyarahkan tentang hukum-hukum haji yang mana dalam Al-Qur’an hanya menyebutkan tentang wajib haji, namun pribadi Nabilah Saw yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji tersebut.
Jadi harapan dan penantian kita terhadap Al-Qur’an dimana ia seharusnya menjelaskan secara detil dan seluruh masalah-masalah yang sekecil apa pun, merupakan harapan dan penantian yang tidak tepat. Dan jika dalam masalah keimamahan dan Ahlulbait As tidak disebutkan satu per satu nama para Imam Maksum As, itu tidak bisa dijadikan sandaran ataupun alasan untuk tidak berpegang pada ajaran dan maktab Ahlulbait As, sebagaimana halnya bahwa karena Al-Qur’an tidak menyebutkan shalat Zhuhur itu adalah 4 rakaat, maka boleh melakukannya dengan dua rakaat. Atau karena Al-Qur’an tidak menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan haji itu harus melakukan tawaf sebanyak tujuh kali, maka boleh meninggalkannya.
2. Pada permasalahan seperti ini yang diprediksikan akan banyak yang menentang, sebaiknya dan maslahatnya itu ada pada bahwa Al-Qur’an menjelaskan hal tersebut secara tidak jelas dan tidak transparan, karena ada kemungkinan penentangan terhadap keimamahan Imam Ali As melebar kearah penentangan terhadap Al-Qur’an itu sendiri dan ini sangat berbahaya bagi Umat Islam. Tentunya perlu dicamkan bahwa Allah Swt dalam Al-Qur’an telah berfirman yang artinya:”Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al Dzikr (Al-Qur’an) dan kami pulalah yang akan menjaganya”,[11] salah satu cara dalam menjaga keaslian Al-Qur’an dan keterpeliharaannya dari segala bentuk distorsi dan penambahan atau pun pengurangan adalah dijelaskan serupa mungkin sehingga motivasi dan niat orang-orang munafik yang berlagak muslim untuk mengaburkannya itu dilenyapkan, sehingga minimalnya kalau ada seorang atau kelompok –dikarenakan hawa nafsu dan ikhtilaf serta adanya motifasi kuat untuk merubah dan mendistorsi– merubah Al-Qur’an tersebut tidak merubahnya sesuai dengan seleranya dan dengan demikian nilai dan kehormatan Al-Qur’an pun bisa terjaga dan tidak dicemooh.[12]
Ayatullah Muthahari, dalam pemaparannya, mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan cara berikut ini: ”Masalah bahwa mengapa Al-Qur’an tidak menjelaskan keimamahan dan khilafah Imam Ali As dengan menyebutkan nama beliau? Mereka memberi jawaban Pertama: Al-Qur’an itu pada dasarnya hanya menjelaskan seluruh permasalahan itu dalam bentuk yang universal, Kedua: Rasulullah Saw atau Allah Swt tidak menghendaki dalam masalah ini, dimana pada akhirnya hawa nafsu pun akan turut campur, sebuah persoalan dijelaskan dalam bentuk seperti ini. Buktinya bahwa mereka tetap berkeras kepala mencoba menerangkan dan bahkan berijtihad –terkait bentuk penjelasan tersebut– lalu mengatakan hal seperti bahwa yang dimaksud Rasulullah Saw adalah demikian dan demikian; yakni kendatipun ada sebuah ayat yang secara khusus dan jelas berbicara tentang masalah ini, mereka tetap akan berusaha menjelaskan dan menafsirkannya sedemikian mungkin (sesuai dengan selera masing-masing). Rasulullah Saw dalam sabdanya menyatakan dengan sangat jelas bahwa:”haadzaa ‘aliyun maulaahu” (ini Ali As sebagai pemimpinnya); apakah Anda masih tetap menginginkan hal yang lebih jelas dari ini?! Terlalu kelewatan, sabda Nabi Saw yang demikian jelas tersebut serta ayat Al-Qur’an yang menjelaskan dengan sempurna dan jelas mengenai masalah itu, pada hari pertama setelah Rasulullah Saw wafat, dibuang begitu saja. Oleh karena itu, pada mukaddimah buku “Khilafat wa Wilâyah” saya menukil kalimat ini bahwa seorang Yahudi pada masa Imam Ali As, hendak mencaci dan mencemooh seluruh kaum Muslimin dengan peristiwa-peristiwa yang sangat naif yang terjadi pada masa awal Islam (dan ada benarnya cacian tersebut), ia berkata kepada Imam Ali As: sebelum nabi kalian dikebumikan, kalian telah berselisih dan berikhtilaf tentangnya. Imam Ali As menjawab: kami tidak berselisih mengenai Rasulullah Saw, perselisihan dan ikhtilaf kami itu tentang suatu perintah yang datang dari Nabi Saw untuk kami, namun kalian ketika kaki kalian masih basah dengan air laut, telah meminta dan mengatakan kepada nabi-nabi kalian: jadikanlah bagi kami tuhan sebagaimana tuhan-tuhan yang mereka miliki. Kemudian Imam Ali As berkata: sungguh kalian ini adalah kaum yang bodoh. Jadi sangat berbeda antara apa yang terjadi pada kami dengan apa yang terjadi pada kalian, kami tidak berselisih tentang Nabi Saw, akan tetapi kami berikhtilaf pada masalah apa maksud dan substansi perintah Rasulullah Saw tersebut? Kedua hal ini sangatlah berbeda dimana suatu pekerjaan yang bagaimanapun juga tetap dilakukannya, penjelasannya di luar juga seperti itu (bukan berarti hakikat seperti itu), mereka berkhayal bahwa maksud Nabi Saw seperti ini, dan pada akhirnya ucapan Nabi Saw tersebut dipelintir sedemikian rupa dan atau menyatakan bahwa ayat Al-Qur’an yang sangat jelas ini dikesampingkan, atau mereka mendistorsi Al-Qur’an tersebut.[13]
Jadi dapat dikatakan bahwa poin asli dari tidak adanya penyebutan secara jelas nama para Imam Maksum As dan atau minimalnya nama Imam Ali As adalah guna menjaga dan memelihara keutuhan dan orisinalitas Al-Qur’an, sebagaimana Anda perhatikan pada ayat-ayat tathhir[14] dan tabligh[15] dan wilâyah [16] yang terletak di antara ayat-ayat yang ada kaitannya dengan istri-istri Nabi Saw atau hukum-hukum atau tiadanya pertemanan Ahli Kitab, dimana nampaknya tidak punya relasi sama sekali dengan wilâyah para Imam As yang suci dan Imam Ali As, namun seorang peneliti dan periset dan objektif bisa dengan sedikit teliti memahami bahwa konteks bagian ayat ini terpisah dengan ayat yang ada sebelum dan sesudahnya dikarenakan terdapat istilah innamâ (hanya) di dalam ayat tersebut.[17][]
[1] . Ibnu al Bithriq, al ‘Umdah, hal. 121 dan 133; Sayid Hasyim Buhrani, Ghâyah al-Marâm, hal. 320; Allamah Amini, al Ghadir, jil. 2, hal. 278.
[2] .hadits ini mutawatir dan ada dalam kitab-kita syi’ah dan sunni. Dalam kitab al Ghadir disebutkan para penukil hadits ini tahap pertahap dari abad 1 sampai abad 14 dimana yang paling awal ada 60 orang dari sahabat Nabi Saw yang dalam kitab-kitab ahlusunnah merupakan perawi hadits ini dan nama mereka itu tercatat dalam kitab-kita tersebut. Dan juga dalam kitab ‘Abaqât Mir Hamid Husein, terbukti akan kemutawatiran hadits al-Ghadir. Al-Ghadir, jil. 1, hal 14-114; Ibnu al-Maghaazali, Manâqib, hal 25-26; Murtadha Muthahari, Imâmat wa Rahbari, hal 72-73.
[3] .al ‘Umdah, hal 173-175; Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, jil. 3, hal 32; al Ghadir, jil. 1, hal 51, jil. 3, hal 197-201.
[4] .Mengenai kemutawatiran hadits-hadits tentang keimamahan Imam Ali As telah banyak ditemukan dalam kitab al Ghadir, dan kitab ‘abaqât. Fadhil Qausyaji (salah seorang ulama terkemuka Ahulusnah) tidak menolak kemutawatiran sebagian riwayat-riwayat tersebut. Syarah Qausyaji bar Tajriidul I'tiqâd, Khajah Thusi.
[5] .Muhammad Hasan Hurra Amili, Itsbâtul Hudât, jil. 3, hal 123; Sulaiman bin Ibrahim Qanduzi, Yanâbii’ul Mawaddah, hal 494; Ghâyatul Marâm, jil. 10 hal 267, sesuai yang dinukil Mishbah Yazdi, Âmuzesy ‘Aqâid, jil. 2, hal 185.
[6] .Qs. al-Najm ayat 3 dan 4.
[7] . Fakhru Razi, Tafsir Kabir, jil. 12, hal 25; Tafsir Nemuneh, jil. 4, hal 421-430; Jalaluddin Suyuti, Tafsir Durul Mantsuur, jil. 2, hal 393; juga dalam kitab-kitab hadits seperti: Dzakhâirul ‘Uqba, Muhibuddin Thabari, hal 88; Jalaluddin Suyuti, Lubâbunnuqûl, hal 90; ‘Alauddin Ali al-Muttaqi, Kanzul Ummal, jil. 6, hal 391 dan masih banyak disebutkan dalam kitab-kitab yang lain yang anda bisa meruju ke tafsir nemuneh jil. 4, hal 425.
[8] .Murtadha Muthahari, Tahlile az Kitâb-e Imâmat wa Rahbari, hal 38.
[9] .innamaa bermakna hanya (pembatasan, eksklusif): Mukhtashar al-Ma’âni.
[10] .Kulaini, al-Kâfi, kitab al-Hujjah, bab mâ nashsh Allahu wa Rasuluhu ‘alal Aimmati Waahidan Fawâhidan, jil. 1.
[11] .Hadavi Tehrani, Mabâni Kalâmi Ijtihâd, jil. 2
[12] .Ibid.
[13] . Imamat wa Rahbari, hal 109-110 (cetakan ke 27)
[14] .Qs. al-Ahzab (33): 33.
[15] .Qs. al-Maidah (5):67.
[16] .Qs. al-Maidah (5):55.
[17] . Hadavi Tehrani, Mabâni Kalâmi Ijtihâd, jil. 2.
Makna “al-Qurba”
Makna “al-Qurba” pada ayat 23 surah Syura
Apabila maksud pembicara dari sebuah redaksi atau kata-kata yang digunakan di dalamnya tidak jelas, pada setiap proposisi dan kalimat, maka ia harus ditelusuri pada indikasi-indikasi (qarâin) yang dapat menjelaskan maksud dari ucapannya itu. Terkait dengan ayat 23 surah al-Syura “Qul laa as’alukum ‘alaih ajran illa mawaddata fil qurbah” padanya terdapat indikasi-indikasi dan tanda-tanda yang membimbing dan membantu kita untuk memperoleh maksud yang sebenarnya dari firman Allah tentang al-Qurba.
1. Sesuai penjelasan pakar bahasa, redaksi al-Qur’ba bermakna kekerabatan dan kedekatan pada nasab (garis keturunan). Sebagaimana hal ini disebutkan dalam al-Qur’an yang selaras dengan makna ini. Namun selain yang ayat yang menjadi obyek pertanyaan, pada ayat-ayat lainnya, pelbagai redaksi “dzi” atau “dzawi” atau “uli” digunakan padanyaidhâfa (tambahan dan hubungan). Dengan idhâfa (tambahan) ini maka kandungan dzawil qurba itu akan bermakna kekerabatan. Dengan demikian, pada ayat yang menjadi obyek pembahasan para periset memandang redaksi “ahl” atau “dzawi” dan lainya sebagai implisit (muqaddar, tidak tercetuskan dalam ucapan atau tulisan).
Dengan demikian, kita tidak dapat menerima penafsiran bahwa “al-Qurba” itu bermakna kedekatan kepada Allah atau makna yang lainnya.
2. Indikasi-indikasi menjadi bukti atas hal ini bahwa maksud kerabat pada ayat dzawil qurba adalah kerabat nabi dan ayat tidak bermakna bahwa wajib bagi setiap kaum Muslimin untuk mencintai keluarganya sebagai ganjaran risalah.
3. Penyebutan kata kerja “laa as’alukum” merupakan petunjuk bahwa maksud dari “dzawil qurba” di sini adalah kerabat orang yang bertanya. Dan hal ini adalah penentuan pemilik kekerabatan melalui jalan penentuan mansub ilahi (yang disandarkan kepadanya) sebagaimana ayat-ayat 113 surah al-Taubah dan ayat 7 surah al-Hasyr dapat dijadikan contoh dalam hal ini.
4. Dengan sedikit menelisik pada ayat-ayat yang terkait dengan upah risalah maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa maksud dari “al-qurba” adalah Ahlulbait Nabi Saw; karena al-Qur’an dari satu sisi menegaskan adanya tuntutan upah dari Nabi Saw dan menafikan adanya tuntutan dari nabi-nabi lain. Dari sisi kedua, al-Qur’an terkait dengan Nabi Saw menyatakan: Aku tidak meminta upah dari kalian kecuali kecintaan (kalian) kepada keluargaku. Dari sisi ketiga, terkabulkanya doa Nabi Saw dan tuntutan upah risalah. Dari sisi keempat, Allah Swt memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk menyampaikan kepada masyarakat: Upah yang aku minta dari kalian adalah untuk kalian dan upah dan ganjaranku pada Tuhan. Dan dengan melampirkan ayat-ayat ini, kita sampai pada kesimpulan sedemikian bahwa: Dzawil Qurba merupakan jalan Ilahi dan mengayunkan langkah di jalan Ilahi ini adalah untuk kepentingan manusia (itu sendiri) dan mengikuti dzawil qurba merupakan contoh nyata penerimaan seruan Ilahi. Dan pada akhirnya, dari riwayat-riwayat standar dapat kita simpulkan bahwa: Hanya Ahlulbait Nabi Saw yang menikmati keutamaan seperti ini.
5. Terdapat banyak riwayat dari Nabi Saw terkait dengan penafsiran ayat ini dimana yang dimaksud dengan al-qurba di sini adalah Ahlulbait Nabi Saw.
Apabila maksud pembicara dari sebuah redaksi atau kata-kata yang digunakan di dalamnya tidak jelas, pada setiap proposisi dan kalimat, maka ia harus ditelusuri pada indikasi-indikasi (qarâin) yang dapat menjelaskan maksud dari ucapannya itu. Terkait dengan ayat 23 surah al-Syura “Qul laa as’alukum ‘alaih ajran illa mawaddata fil qurbah”[1] padanya terdapat indikasi-indikasi[2] dan tanda-tanda yang membimbing dan membantu kita untuk memperoleh maksud yang sebenarnya dari firman Allah tentang al-Qurba.
1. Redaksi “al-Qurba” sesuai dengan penjelasan pakar bahasa bermakna kedekatan dan kekerabatan pada nasab (garis keturunan).[3] Dalam al-Qur’an digunakan untuk orang-orang yang memiliki kedekatan dan kekerabatan, intinya adalah kekerabatan dan kekeluargaan. Karena itu terkadang redaksi “dzi” yang ditambahkan kepadanya,[4] terkadang “dzawi”[5] dan terkadang dengan lafaz “uli”.[6] Dan hanya sekali datang tanpa tambahan (hubungan). Dan yang satu ini merupakan obyek pertanyaan dalam kesempatan ini “…illla mawaddah fil qurba…” Dengan demikian lafaz seperti “ahl” [7] atau “dzi” atau “dzawi” dan sebagainya sebelum redaksi “al-Qurba” disebutkan secara implisit (muqaddar). Dan makna “al-mawaddah fil qurba”, kecintaan (mawaddah) kepada kerabat dan keluarga Nabi Saw yaitu Ahlulbait Nabi Saw.
Artinya, penafsiran sebagian mufassir yang memaknai “qurba” pada ayat di atas adalah kedekatan kepada Allah Swt,[8] tidak benar adanya.[9] Karena berasaskan penafsiran ini, redaksi qurba akan bermakna yang mendekatkan bukan kedekatan dan hal ini berseberangan dengan sesuatu yang disampaikan oleh pakar bahasa.
Di samping itu, makna sedemikian akan menyebabkan kekaburan pada ayat. Sebagai kesimpulannya, kaum musyrikin tidak dapat menjadi obyek bicara ayat. Karena mereka tidak mengingkari kedekatan kepada Allah, melainkan menyembah berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka pandang sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan.[10]
Boleh jadi dikatakan bahwa “al-qurba” merupakan mashdar (derivat) dan mashdar ini bermakna kedekatan dan kekerabatan bukan bermakna kerabat. Dan “fii” juga bermakna kausatif (sababiyat). Sesuai dengan pandangan ini, terdapat tiga kemungkinan dalam kandungan ayat tersebut:
A. Obyek bicara ayat adalah Quraish yang diminta dari mereka: Apabila kalian tidak beriman kepada Nabi Saw, setidaknya kalian mecintainya dan tidak mengganggunya karena kekerabatan dan kedekatan kepadanya.
B. Obyek bicara ayat adalah kaum Anshar dan diminta untuk mecintai mereka karena kekeluargaan dan kekerabatan Nabi Saw dengan mereka.[11]
C. Obyek bicara ayat adalah kaum Quraish dan maksud “al-mawaddah fil qurba” adalah kecintaan Nabi Saw bukan kecintaan Quraish. Artinya wahai Quraish aku tidak menghendaki upah dari kalian. Namun kecintaanku kepada kepada kalian karena kekerabatan kalian kepadaku. Dan hal ini tidak memberikan izin kepadaku untuk bersikap acuh tak acuh kepada kalian dan kekeluargaanku kepada kalian menuntutku untuk menghidayai kalian bukan mengambil upah dari kalian.
Ketiga kemungkinan ini kendati sepintas kelihatan masuk akal dan elok dipandang mata, namun dengan sedikit lebih teliti maka akan menjadi jelas bahwa tidak satu pun dari tiga kemungkinan ini benar adanya. Karena apabila yang dimaksud adalah kafir Quraish, mereka tidak mengambil apa pun dari Nabi Saw sehingga harus menyerahkan upah. Dan apabila yang dimaksud adalah orang-orang Quraish yang beriman kepada Nabi Saw, dalam hal ini kemarahan tidak dapat digambarkan sehingga dituntut dari mereka untuk melenyapkan kemarahan mereka sebagai upah risalah, karena itu kemungkinan pertama akan tertolak.
Demikian juga, persahabat kaum Anshar dengan Nabi Saw sedemikian jelas sehingga tidak ada pun orang yang tidak tahu tentangnya. Karena itu, tidak ada maknanya bahwa Nabi Saw meminta mereka untuk mecintainya karena kekerabatan jauh yang ada di antara mereka. Terlebih orang Arab tidak terlalu memandang penting kekerabatan dari pihak ibu.[12] Dan Islamlah yang memberikan perhatian penting terhadap masalah ini. Karena itu, kemungkinan kedua tidak memiliki landasan rasional yang dapat diterima. Adapun dalam mengkritisi kemungkinan ketiga dapat dikatakan bahwa: Apakah kemungkinan ini tidak berseberangan dengan kedudukan Nabi Saw? Bukankah al-Qur’an berulang kali menegaskan bahwa tugasmu (Muhammad) hanyalah mengajak. Adapun memberikan petunjuk dan menghidayai itu adalah tugas Allah Swt dan Nabi Saw tidak boleh bersedih hati karena perlakuan orang-orang kafir. Bagaimana dapat dipercaya bahwa Nabi Saw karena kekerabatan, beliau memberikan petunjuk kepada sebagian orang dan lantaran kemarahan dan ketidaksukaan kepada sebagian lainnya, menghindar tidak memberikan petunjuk kepada mereka.[13]
2. Kini yang dimaksud dengan “al-Qurba” telah jelas maka pertanyaan yang mengemuka sekarang adalah siapa yang dimaksud dengan orang-orang dekat dan para pemilik kekerabatan dan kedekatan pada garis keturunan? Jawabannya adalah Ahlulbait Nabi Saw yang merupakan maksud utama ayat ini. Hal itu dikarenakan:
Pertama, teridentifikasinya mansub ilaihi (yang disandarkan padanya), merupakan sebuah indikasi untuk menentukan pemilik kedekatan. Terkadang, mansub ilaihi disebutkan pada ucapan dan hal ini sendiri dapat menjadi sebuah tanda bahwa siapa yang dimaksud dengan keluarga dan kerabat. Misalnya dalam al-Qur’an disebutkan “Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (mereka), sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam.” (Qs. Al-Taubah [9]:113) Penyebutan “nabi” dan “orang-orang yang beriman” adalah bukti atas poin ini bahwa yang dimaksud dengan “uli qurba” adalah orang-orang dekat setiap orang. Atau pada sebuah ayat “Setiap harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota itu adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul” (Qs. Al-Hasyr [59]:7) Redaksi “kepada rasul” merupakan indikasi bahwa yang dimaksud dengan “lidzil Qurba” adalah kerabat dan orang-orang dekat Rasulullah Saw. Pada ayat “Katakanlah (Wahai Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku ini kecuali kecintaan kepada keluargaku” juga terdepannya kata kerja “aku tidak meminta” merupakan sebuah tanda bahwa yang dimaksud “al-Qurba” adalah orang-orang dekat yang meminta (al-sail).[14]
Karena itu pada ayat mawaddah sendiri merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud “al-qurba” itu adalah Ahlulbait dan orang-orang dekat Rasulullah Saw. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa ayat ini menandaskan kecintaan kepada orang-orang dekat (Rasulullah) dipandang sebagai upah risalah. Dan ayat tersebut meminta kepada kaum Muslimin untuk mencintai keluarga Rasulullah Saw.[15]
Kedua, ayat-ayat yang berkenaan dengan upah risalah dalam al-Qur’an termasuk beberapa permasalahan di bawah ini:
B. Terkait dengan pribadi Rasulullah Saw disebutkan bahwa: Aku tidak menginginkan upah dari kalian kecuali kecintaan kepada keluargaku.
C. Juga dijelaskan bahwa: Upahku adalah bagi orang-orang yang menerima seruanku dengan pilihan mereka.[18]
D. Pada ayat lainnya disebutkan: “Katakanlah, “Upah apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. Saba [34]:47)
Dengan menyandingkan ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Saw juga seperti para nabi yang lainnya, tidak menginginkan upah untuk dirinya sendiri, melainkan kecintaan kepada Ahlulbaitnya merupakan jalan menuju ke haribaan Tuhan. Dan sejatinya kecintaan ini adalah untuk manusia itu sendiri. Karena kecintaan ini merupakan gerbang untuk memasuki masalah imamah, khilafah, pengganti Rasulullah Saw dan pemberian petunjuk bagi manusia. Kecintaan ini merupakan perkara berpulang pada masalah pemenuhan dan ajakan.[19]
Dari satu sisi, “ajr” merupakan satu redaksi yang diperuntukkan baik untuk “ajr duniawi” dan juga “ajr ukhrawi”. Dan apa yang telah dinafikan pada ayat-ayat ini adalah “ajr duniawi.” Karena pada ayat-ayat ini disebutkan bahwa aku tidak meminta upah dari kalian, secara lahir menandaskan pada upah dan ganjaran duniawi. Dan kehidupan Nabi Saw menjadi bukti dan saksi atas makna ini[20] bahwa Nabi Saw tidak mengejar upah dan ganjaran duniawi.
Dari sisi lain, upah dan ganjaran hakiki, mengejewantah ketika memberikan manfaat bagi yang menerimanya, sementara mawaddah (cinta berlebih, isyq) dan mahabba (cinta) terhadap dzawilqurba adalah untuk kepentingan pecinta bukan untuk kepentingan Nabi Saw. Karena kecintaan terhadap dzawilqurba akan menyebabkan kecintaan, pada kehidupannya mengikuti dzawilqurba, dan menjadikanyna sebagai teladan dan menjauhkan dirinya dari perangkap setan.[21]
Karena itu, Nabi Saw tidak menghendaki upah dan ganjaran duniawi. Dan apabila beliau menghendaki kecintaan masyarakat kepada dzawilqurba hal ini bukan merupakan upah dan ganjaran hakiki karena al-Qur’an menegaskan bahwa keuntungan dari kecintaan ini adalah untuk manusia.
Sekarang kita harus mengajukan pertanyaan bahwa kecintaan kepada siapa dan mengikuti siapa yang memberikan keuntungan kepada masyarakat? Dan kecintaan kepada siapa yang merupakan contoh-contoh terkabulkannya doa Nabi Saw?
Apakah mawaddah dan mahabbah kepada orang-orang yang ternodai dengan kebodohan dan kesesatan dapat menjadi faktor penyelamat orang lain? Dan apakah apabila orang buta yang menuntun orang buta dapat menyampaikan manusia kepada akhir tujuannya?
Petunjuk Ilahi untuk seluruh manusia merupakan upah risalah. Tentu saja petunjuk Ilahi ini adalah untuk kepentingan dan keuntungan manusia. Dan perkara ini juga berada pada pancaran petunjuk (hidayah) dapat terealisir adalah jiwa dan diri Rasulullah Saw,[22] pelita hidayah,[23] bahtera keselamatan,[24] gerbang ilmu,[25] jalan kebenaran dan sebagainya. Dan apakah orang-orang sedemikian bukan lain Ahlulbait Rasulullah Saw.
Ketiga, terdapat banyak riwayat yang dinukil oleh kedua mazhab dalam masalah ini secara jelas dan tegas menjelaskan maksud “al-qurba,” sebagaimana dibawah ini:
1. Hakim Huskani dalam menjelaskan ayat ini menukil sebuah riwayat yang menjelaskan siapa saja yang dimaksud dengan “dzawil qurba”[26] Misalnya Ibnu Abbas berkata, “Tatkala ayat “Katakanlah (Muhammad) Aku tidak meminta upah atas apa yang kuserukan kecuali kecintaan kepada al-qurba,” diwahyukan, para sahabat Rasulullah Saw bertanya: Siapakah orang-orang yang dititahkan Tuhan untuk kami cintai? Rasulullah Saw bersabda: “Ali, Fatimah, kedua putra dari mereka.”[27]
2. Suyuthi dalam menafsirkan ayat ini menukil sebuah riwayat dari Nabi Saw yang menjelaskan: Maksud ayat ini adalah (hendaknya) kalian menjaga hakku dan Ahlulbaitku.”[28]
3. Ahmad bin Hanbal dalam Fadhail al-Shahaba dan Qurthubi dalam menafsirkan ayat (mawaddah) menukil riwayat dari Nabi Saw dimana yang dimaksud (al-Qurba) adalah Ali, Fatimah, dan kedua putranya.”[29]
4. Zamakhsyari[30] dan Fakhrurazi[31] dengan bersandar pada sebuah riwayat yang dinukil dari Nabi Saw bahwa ayat “dzawil qurba” dikhususkan kepada Ali, Fatimah dan kedua putranya.”
Namun banyak kritikan dan isykalan yang diajukan terkait dengan penafsiran “al-mawaddah fi al-qurba” bahwa itu bermakna kecintaan terhadap Ahlulbait As. Di antaranya tidak dapat diterima bahwa yang dimaksud dengan “al-mawaddah fi al-qurba” adalah Ahlulbait As. Karena ayat yang disebutkan pada surah Syura dan apakah surah ini merupakan surahMakkiyah, dimana Fatimah Zahra, Hasan dan Husain belum atau tidak ada (ketika itu) sehingga kecintaan kepada mereka menjadi upah risalah!
Dalam menjawab pertanyaan ini harus dikatakan bahwa: Pertama, mayoritas penafsir berkata bahwa keempat ayat surah al-Syura ini merupakan surah Madani bukan Makkiyah. Kedua, banyak riwayat yang memandang bahwa pewahyuan ayat ini berlangsung di Madinah. Ketiga, yang menjadi kriteria surah tergolong Makkiyah atau tidak bukan terletak pada pra hijrah atau pasca hijrah, boleh jadi setelah hijrah terdapat surah yang diturunkan di Makkah, misalnya para hajjatul widâ’ dan setelah kelahiran Fatimah, Hasan, dan Husain.[32]Untuk menjawab kritikan dan isykalan ini secara detil kami akan alokasikan pada kesempatan yang lain.[]
Kami cukupkan tulisan ringkas ini di sini dan mereka yang tertarik untuk meriset dan menelaah lebih jauh kami persilahkan untuk merujuk kepada sumber-sumber di bawah ini:
1. Ihyâ al-Mayyit bifadhâil Ahlulbait, Suyuthi, hal. 8.
2. Al-Shawâiq al-Muhriqah, Ibnu Hajar, hal. 101.
3. Al-Mizân, Allamah Thabathabai, jil. 18, hal. 51-53.
4. Ahlulbait, Maqâmuhum, Manhâjuhum, Masâruhum, hal. 14-19.
5. Payâm-e Qur’ân, Makarim Syirazi, jil. 9, hal. 225-237
6. Tafsir Qurthubi, jil. 8, hal. 5843, jil. 16, hal. 21-22.
7. Tafsir Nemune, jil. 7, hal. 174 dan jil. 11, hal. 369, dan jil. 12, hal. 95.
8. Jami’ al-Bayân, Thabari, jil. 25, hal. 16.
9. Mustadrak al-Shahiain, Hakim Naisaburi, jil. 3, hal. 173.
10. Hilyat al-Awliyâh, Hafiz Abu Nu’aim Isfahani, jil. 3, hal. 201.
11. Dzakhâir al-Uqba’, Muhibuddin Thabari, hal. 138.
12. Ruh al-Ma’âni, jil. 25, hal. 32.
13. Kanz al-‘Ummâl, jil. 1, hal. 118.
14. Majma’ al-Bayân, jil. 9, hal. 28, 29, 50; jil. 7 dan 8, permulaan surah al-Mukmin, hal. 512.
15. Majma’ al-Zawâid, jil. 9, hal. 168.
[1]. “Katakanlah (Wahai Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku ini kecuali kecintaan kepada keluargaku.”
[2]. Indikasi-indikasi (qarain) terdiri dari dua jenis: Indikasi yang terdapat pada proposisi atau kalimat atau berada di luar namun terpendam ucapan padanya dimana indikasi semacam ini disebut sebagai indikasi bersambung (qarinah muttasil). Dan indikasi yang terdapat pada ucapan dan belum terjamah dan pembicara menyampaikan maksudnya pada kesempatan lain. Indikasi semacam ini disebut sebagai indikasi terputus (qarinah munfasil).
[3]. Maqaiis al-Lugha menyebutkan: “Fulan dzu qirabati. Huwa man yaqrub minka rahiman.” (Si fulan memiliki kekerabatan. Dia adalah orang yang dekat kepadamu secara nasab) Dan melanjutkan “al-Qurba wa al-Qirabah be ma’na wahid.” (al-Qurba dan qirabah itu bermakna tunggal) Lisan al-Arab dalam hal ini menjelaskan: “Qirabah dan qurba bermakna kekerabatan dalam nasab. Dan yang lain berkata, “al-qurbâ (keluarga) dalam nasab dan al-qurbatu pada kedudukan. Dan aslinya keduanya adalah satu. Aqrab al-Mawarid, jil. 2, hal. 978.
[4]. “Wa bil walidain ihsana wa dzil qurba wa al-yatama” (Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, Qs. Al-Baqarah [2]:83)
[5]. “Wa ata al-Mal ‘ala hubbihi dzawi qurba wa al-yatama” (Dan para nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, Qs. Al-Baqarah [2]:177)
[6]. “Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (mereka)”Qs. Al-Taubah [9]:113)
[7]. Zamakhsyari dalam hal ini menjelaskan: “al-Qurba adalah mashdar sepert zulfa dan al-busyra, yang bermakna al-qirabah dan maksudnya pada ayat adalah “ahlul qurba”. Al-Kassyaf, jil. 3, hal 81, terkait surah al-Syura ayat 23.
[8]. “Mencintai segala perkara yang mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan” adalah tafsir atas kandungan ayat ini.
[9]. Namun pandangan ini memiliki isykalan lainnya yang telah dibahas pada tempatnya, misalnya redaksi mahabat dan mawaddah tidak selaras dengan makna ini; karena apa yang menyebabkan kedekatan kepada Allah adalah menunaikan shalat dan sebagianya, bukan (sekedar) mawaddah dan mahabbat mereka. Di samping itu, memangnya di antara para lawan bicara Nabi Saw tidak menyukai masalah ini dan ayat diturunkan kepadanya… Silahkan lihat al-Mizan, jil. 18, hal. 45-46; Tafsir Maudhu’i Payâm-e Qur’ân, jil. 9, Makarimi Syirazi, hal. 225-237.
[10]. Tafsir al-Mizân, Allamah Thaba-thabai, jil. 18, hal. 45-46.
[11]. Karena Nabi Saw dari pihak ibu dan dari pihak Salma binti Zain al-Naijariyah memiliki kekerabatan dengan kaum Anshar.
[12] Misalnya orang-orang Arab berkata:
Banuna banu abnaina wa banatina
Banuhunna abna al-rijal al-abai’d
Putra-putra putri kami adalah putra-putra pria asing
[13]. Al-Mizân, Allamah Thabathabai, jil. 18, hal. 43-45; Tafsir Maudhu’i Payâm-e Qur’ân, jil. 9, hal. 225-237
[14]. Mafâhim al-Qur’ân, Ja’far Subhani, jil. 10, hal. 268-269.
[15]. Kemungkinan ini tidak hanya tidak menyokong ayat ini, namun juga tidak sejalan dengan upah risalah, memangnya seluruh orang Quraish (sekiranya obyek ayat ditujukan kepada kaum Quraish) atau seluruh manusia (apabila obyek ayat ditujukan kepada seluruh manusia) memiliki kekerabatan dengan orang mukmin kemudian melalui kecintaan kepada mereka harus menyerahkan upah risalah. Lihat, Al-Mizan, Allamah Thabathabai, jil. 18, hal. 45; Payam-e Qur’an, jil. 10, hal. 225-237.
[16]. “Dan (dia berkata), “Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepadamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman itu. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku.” (Qs, Hud [11]: 29 & 51); “Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.” (Qs. Al-Syuara [26]: 109, 127, 145, 164 dan 180)
[17]. “Katakanlah, “Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur’an). Al-Qur’an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk umat semesta alam.” (Qs. Al-An’am [6]:90)
[18]. “Katakanlah, “Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan orang yang mau mengambil jalan menuju Tuhan-nya, (dan inilah upahku).” (Qs. Al-Furqan [25]:57)
[19]. Al-Mizân, jil. 18, hal. 42-49; Mafâhim al-Qur’an, jil. 10, hal. 261-274; Payâm-e Qur’ân, jil. 9, hal. 225-237.
[20]. Al-Sirah al-Nabawiyah, jil. 1, hal. 293-294; Syaikh Mufid Ra dalam hal ini berkata: “Perbuatan (amal) harus ditujukan semata untuk Tuhan dan penuh keikhlasan, dan apa yang dilakukan untuk Tuhan, maka ganjarannya pada Tuhan bukan pada yang lain. Dan Nabi Saw pada seluruh hidupnya sendiri demikian adanya. (Tashih al-I’tiqad, hal. 68)
[21]. Imam Shadiq As dalam sebuah riwayat bersabda: “Maa AhabbaLlah Azza wa Jal man ‘ashahu” (tidak mencintai Allah orang yang bermaksiat kepada-Nya) kemudian beliau membacakan syair berikut ini:
Ta’sha Allah wa anta Tuzhir Hubbah
Hadza Muhal fi al-fa’al badi’
Lau kana hubbuka shadiqan laa thatahu
Inna al-mahabbah liman yuhibbu muthi’
Engkau bermaksiat kepada Allah sementara Engkau ungkapkan cinta (kepada-Nya)
Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil bagi orang-orang utama
Sekiranya cintamu itu benar adanya maka engkau pasti mentaati-Nya
Sesungguhnya cinta itu mentaati orang yang dicintainya
(Safina al-Bihar, klausul Hubb)
Mahabbah ditujukan untuk ketaatan dan ketaatan dimaksudkan untuk hidayah dan hal ini merupakan terjawabnya doa yang disebutkan pada ayat 57, surah al-Furqan.
[22]. Pada ayat Mubâhâlah, Ali disebut sebagai jiwa Nabi Saw.
[23]. “Inna al-Husain misbah al-Huda wa Safinat al-Najâh” (Sesungguhnya Husain adalah pelita hidayah dan bahtera keselamatan. (Safinah al-Bihar, jil. 1, hal. 387.)
[24]. Rasulullah Saw: Matsal Ahlubaiti fiikum matsala safinatu Nuh, man Rakibahâ najah” (Permisalan Ahlulbaitku bagi kalian adalah laksana bahterah Nuh, barangsiapa yang menaikinya akan selamat), Lihat Kanz al-‘Ummâl, jil. 6, hal. 216; Ahlulbait Maqâmuhum, Manhâjuhum, Masâruhum, hal. 44-46.
[25]. Rasulullah Saw bersabda: Ana madinatul Ilm wa ‘Aliyin Bâbuha..(Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya)
[26]. Dalam doa Nudbah disebutkan: Fakanû hum al-Sabil ilaika wa al-maslak ilaa ridwanik” (Mereka adalah jalan kepada-Mu dan wahana kepada keridhaan-Mu)
[27]. Syawâhid al-Tanzil, jil. 2, hal. 130, 131, 135, 140.
[28]. Al-Durr al-Mantsur, jil. 6, hal. 7
[29]. Ihqâq al-Haq, jil. 3, hal. 2; Ghâyat al-Marâm, tafsir ayat.
[30]. Tafsir al-Kasysyâf, jil. 4, hal. 220-221.
[31]. Tafsir Kabir Fakhrurazi, jil. 27, hal. 165-167.
[32]. Tafsir Maudhui Qur’ân Karim, Abdullah Jawadi Amuli, jil. 8, hal. 341.
Langgan:
Catatan (Atom)